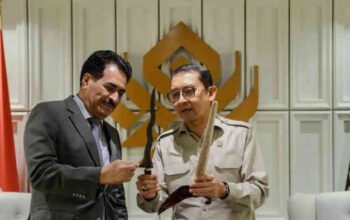JAKARTA — Di tengah langit biru Sulawesi Selatan, polemik terbang lebih tinggi dari jet pribadi yang membawa Nasaruddin Umar ke Takalar. Sang Menteri Agama menegaskan kehadirannya dalam penerbangan jet pribadi tersebut murni karena undangan keluarga untuk meresmikan madrasah. Publik, seperti biasa, tidak berhenti di kata “keluarga”.
“Tiba-tiba ya pesawatnya begitu. Masa saya tidak datang? Udah deh,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Rabu malam (18/2/2026). Jawaban yang santai, nyaris sekelas obrolan arisan, tetapi efeknya langsung menabrak radar etika publik.
Ketika ditanya ihwal potensi gratifikasi, ia menjawab pendek, “Enggak tahu, terserah.”
Dalam politik Indonesia, kata “terserah” sering kali bukan akhir kalimat melainkan awal perdebatan panjang.
Nasaruddin menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Takalar, Sulawesi Selatan, pada Ahad (15/2/2026). Gedung tersebut merupakan fasilitas keagamaan dan pendidikan yang didirikan oleh Yayasan OSO milik Oesman Sapta Odang.
Acara itu turut dihadiri Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, jajaran Forkopimda, serta ratusan tokoh agama dan masyarakat.
Masalahnya bukan pada peresmian. Masalahnya ada pada moda transportasi: jet pribadi dengan nomor registrasi PK-RSS.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan pesawat itu dimiliki Natural Synergy Corporation yang berbasis di British Virgin Islands wilayah yang dikenal sebagai suaka pajak. Basis data International Consortium of Investigative Journalists mencatat perusahaan tersebut masih aktif, dengan OSO sebagai pemegang saham sejak 2008.
Kementerian Agama mengonfirmasi pesawat itu memang fasilitas dari OSO.
Di titik ini, publik mulai bertanya: undangan keluarga boleh saja, tetapi fasilitas mewah dari tokoh politik dengan jejaring bisnis global apakah sesederhana silaturahmi?
Indonesia Corruption Watch bersama Trend Asia menghitung nilai penerbangan pulang-pergi Jakarta–Makassar–Bone–Makassar–Jakarta selama sekitar lima jam mencapai Rp 566 juta.
Emisi karbon yang dihasilkan? Sekitar 14 ton CO₂.
Bagi aktivis iklim, angka ini bukan sekadar nominal, melainkan simbol. Zakki, peneliti Trend Asia, menyebut jet pribadi sebagai moda transportasi paling polutif. Terlebih, rute Makassar–Bone dapat ditempuh melalui jalur darat atau penerbangan komersial.
Ironinya, Menteri Agama sebelumnya pernah menggunakan pesawat komersial untuk rute serupa. Artinya, alternatif tersedia.
Dalam narasi perubahan iklim, teladan pejabat publik sering lebih nyaring dari khutbah panjang.
Secara hukum, sorotan mengarah pada ketentuan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Pasal 12B menyatakan setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi bernilai Rp10 juta atau lebih dan tidak dapat membuktikan bahwa itu bukan suap, dapat dipidana minimal 4 tahun hingga seumur hidup.
Nilai penerbangan Rp 566 juta jelas melampaui ambang batas.
Nasaruddin menegaskan pihak pengundang tidak memiliki hubungan resmi dengan kementerian. “Apanya gratifikasi?” katanya. Ia menyebut hubungan kekeluargaan sebagai dasar moral penerimaan fasilitas tersebut.
Namun dalam etika jabatan publik, konflik kepentingan tak selalu lahir dari relasi formal. Ia sering muncul dari ruang abu-abu: kedekatan personal, jaringan politik, dan fasilitas mewah yang kebetulan “tersedia”.
Kasus ini menempatkan Menteri Agama di simpang tiga: hukum, etika, dan persepsi publik.
Secara normatif, pembuktian gratifikasi memerlukan proses hukum. Namun secara etis, pejabat publik dituntut menjauhi segala bentuk fasilitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apalagi dari figur politik berpengaruh.
Di tengah krisis iklim, seruan kesederhanaan bukan lagi retorika moral, melainkan kebutuhan ekologis. Di tengah krisis kepercayaan, transparansi bukan pilihan, melainkan keharusan.
Jet pribadi mungkin mendarat mulus di landasan. Tetapi polemiknya masih terus mengudara.
Dan publik, seperti biasa, menjadi menara pengawas terakhir.***