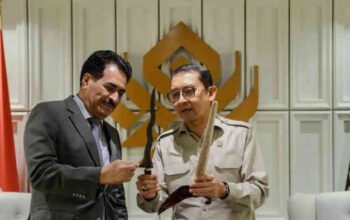WAWAINEWS.ID — Dunia mengenal Atlantis sebagai negeri yang hilang. Kisahnya besar, dramatis, dan jauh di seberang lautan. Tapi di Lampung Timur, tepatnya di Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, ada cerita serupa lebih sunyi, lebih membumi, dan tentu saja tidak kalah misterius. Namanya bukan Atlantis. Warga menyebutnya Tiyuh Silep: kampung yang hilang.
Istilah silep dalam bahasa Lampung berarti menghilang. Bukan hancur, bukan pindah, melainkan ada tapi tiada tak kasatmata, tak tersentuh, namun diyakini tetap menghuni ruang yang sama dengan manusia biasa. Tiyuh Silep inilah yang oleh sebagian warga dipercaya sebagai Negeri Ider Budi, kampung pertama yang kini lebih dikenal sebagai Tiyuh Tuho.
Cerita ini hidup dari tutur ke tutur. Tidak tercatat di arsip negara, tidak masuk buku sejarah resmi, tapi hafal di kepala orang-orang tua. Dan seperti banyak kisah kebudayaan lain, justru di situlah kekuatannya.
Konon, hilangnya Tiyuh Silep berkaitan dengan satu keputusan besar: menolak memeluk agama Islam. Bagi sebagian orang modern, ini terdengar hitam-putih. Namun bagi masyarakat masa lalu, keyakinan adalah soal identitas bukan sekadar pilihan administratif.
Dalam legenda setempat, Negeri Ider Budi dipimpin oleh Raka Jimat atau Datuk Binjai, tokoh sakti mandraguna. Cucu beliau, Tuan Sayih, bersama ayahnya Tuan Tsigaret dan kakak iparnya Puanan Balak, telah lebih dulu memeluk Islam. Tuan Sayih pun berniat mengajak sang kakek meninggalkan kepercayaan lama animisme dan Budha dan menerima agama baru yang diyakininya.
Ajakan itu ditolak. Tegas. Tanpa negosiasi.
Akhirnya, dilakukan jalan tengah: wilayah dipisah. Negeri Ider Budi (Tiyuh Tuho) tetap dengan keyakinan lama, sementara pengikut Islam pindah ke Tiyuh Ketanggai Nyapah, kawasan yang kini dikenal sebagai bagian dari Gunung Sugih Besar. Sebuah kompromi yang, dalam bahasa sekarang, terdengar cukup demokratis.
Namun cerita tidak berhenti di situ.
Dikisahkan, Tuan Sayih terus berupaya. Hingga suatu malam, ia mengelilingi Negeri Ider Budi sambil berzikir, membaca asma Allah. Malam itu, menurut cerita, bukan hanya sunyi tetapi menentukan. Seketika, penduduk Negeri Ider Budi disebut mokso: menghilang dari pandangan manusia biasa.
Sejak saat itulah kampung itu disebut Tiyuh Silep. Kampung yang dulunya ramai, kini senyap. Penghuninya diyakini masih ada, tetapi tidak lagi terlihat. Apakah sampai sekarang masih ada? Seperti hampir semua kisah besar, jawabannya satu: Wallahualam.
Kepercayaan terhadap Tiyuh Silep begitu kuat. Dulu, saat melintas kawasan itu, orang tidak boleh menyebut asma Allah bahkan sekadar refleks ketika tersandung batu. Larangan yang terdengar ganjil, bahkan kontradiktif, namun dipercaya sebagai bentuk penghormatan terhadap wilayah yang dianggap “berbeda hukum alamnya”.
Hingga tahun 1970-an, cerita-cerita aneh masih sering terdengar. Ada suara orang berbincang, bunyi tarian adat Lampung, hingga kisah warga yang bisa “meminjam” perlengkapan adat secara gaib untuk hajatan.
“Dulu tiap ada hajatan, ada saja cerita orang meminjam alat adat dari sana. Bahkan kadang terdengar suara tari-tarian dari arah Tiyuh Tuho,” tutur Udin, warga setempat, sambil tersenyum tipis antara percaya dan pasrah.
Bagi warga Gunung Sugih Besar, Tiyuh Silep bukan sekadar angker. Ia dihormati. Tidak diganggu, tidak dirusak, tidak dijadikan bahan uji nyali. Sebab melanggar pantangan, kata mereka, bukan soal berani atau tidak tetapi soal siap menanggung akibat.
Menariknya, di balik semua kisah mistis, terdapat cerita penting tentang masuknya Islam di Gunung Sugih Besar. Berbeda dari wilayah Lampung lain yang kerap dikaitkan dengan Banten dan Maulana Hasanuddin, desa ini memiliki narasi sendiri. Islam dipercaya masuk lebih awal, dibawa oleh Tuan Sayih, Puanan Balak, dan Tuan Tsigaret.
Tuan Sayih bahkan disebut sebagai orang pertama yang membangun langgar (mushalla) di desa tersebut cikal bakal masjid yang masih digunakan hingga kini. Ia mengenal Islam bukan dari darat, melainkan dari laut, dalam sebuah kisah yang nyaris epik.
Dikisahkan, Tuan Sayih bertemu empat orang alim yang sedang salat di tengah laut. Ia mencoba menguji kesaktian mereka dengan pusaka, namun tak satu pun mempan. Senjata-senjatanya dibuang ke laut. Setelah salat, keempat orang itu berkata: semua ilmu kesaktian tak ada gunanya tanpa iman. Tuan Sayih pun diajak masuk Islam dan dibawa ke Mekah.
Sepulangnya, ia membawa mimbar dan tongkat khotbah, yang menurut cerita masih tersimpan rapi di masjid Gunung Sugih Besar hingga kini. Sebuah artefak yang bagi warga bukan sekadar benda, melainkan simbol perjalanan iman.
Tiyuh Silep, dengan segala kisahnya, mungkin tidak akan pernah masuk buku sejarah nasional. Tapi ia hidup sebagai sejarah budaya, tempat mitos, keyakinan, dan identitas bertemu. Ia mengajarkan satu hal: tidak semua yang hilang benar-benar lenyap sebagian hanya berpindah tempat, dari dunia kasatmata ke ingatan kolektif.
Dan selama cerita itu masih dituturkan, Tiyuh Silep akan tetap ada. Diam. Tapi tidak pernah kosong.
Catatan Budaya Redaksi Wawai News: disusun dari cerita tutur berbagai narasumber, sebagai upaya merawat ingatan, bukan menakar kebenaran.