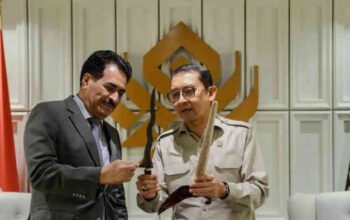JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut positif diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang resmi menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. MUI menilai langkah ini sebagai tonggak penting menuju kemandirian dan kedaulatan hukum nasional, sekaligus simbol lepas dari bayang-bayang produk hukum penjajah.
“Artinya, kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial menuju kemandirian dan kedaulatan hukum nasional. KUHP baru menjadi payung hukum pidana untuk melindungi masyarakat,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, sebagaimana dilansir pada MUI Digital di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Namun, di balik apresiasi tersebut, MUI juga menyisipkan catatan kritis ibarat memberi tepuk tangan sambil mengangkat alis. Salah satu pasal yang disorot adalah potensi pemidanaan terhadap nikah siri dan isu poligami.
Nikah Dicatatkan, Bukan Dipenjarakan
Prof Ni’am menjelaskan, negara memang berkepentingan agar setiap peristiwa perkawinan dicatatkan demi kepastian administrasi dan perlindungan hak keperdataan serta hak sipil warga negara. Namun, pendekatannya seharusnya mendorong kesadaran, bukan menghadirkan ancaman pidana.
“Pendekatannya adalah keaktifan masyarakat untuk mencatatkan pernikahan. KUHP mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang yang sah, misalnya menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan,” jelasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat itu menegaskan bahwa dalam hukum Islam, perempuan yang masih berstatus istri orang lain jelas tidak boleh dinikahi. Di sinilah pidana bisa berlaku.
“Kalau poliandri istri yang masih terikat perkawinan lalu menikah dengan laki-laki lain—itu bisa dipidana. Tapi itu tidak berlaku untuk poligami,” tegasnya.
Merujuk Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan fikih, Prof Ni’am mengingatkan adanya kategori perempuan yang haram dinikahi (al-muharramat minan nisa’), seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.
Jika larangan ini dilanggar dengan sengaja, barulah pidana memiliki relevansi. Namun, MUI menilai pemidanaan nikah siri tidak tepat.
“Tidak semua nikah siri dilakukan untuk menyembunyikan sesuatu. Di lapangan, banyak yang menikah siri karena persoalan akses dan kendala administrasi,” ujarnya.
Ketua Umum Majelis Alumni IPNU ini menegaskan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah peristiwa keperdataan, sehingga penyelesaiannya pun seharusnya keperdataan, bukan penjara.
“Memidanakan urusan yang hakikatnya perdata perlu diluruskan. Tapi secara umum, MUI tetap mengapresiasi KUHP baru yang menggantikan warisan kolonial,” sambungnya.
Pasal 402 dan Kekhawatiran Tafsir Serampangan
Prof Ni’am juga menyoroti Pasal 402 KUHP yang mengatur pemidanaan orang yang melangsungkan perkawinan dengan mengetahui adanya penghalang sah. Menurutnya, pasal ini sebenarnya jelas dan aman, karena memiliki batasan tegas.
“Dalam Undang-Undang Perkawinan, sahnya pernikahan merujuk pada ketentuan agama. Dalam Islam, penghalang sah itu jika perempuan masih terikat perkawinan dengan orang lain. Keberadaan istri bagi laki-laki bukan penghalang sah,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa nikah siri yang sah secara agama dan memenuhi rukun tidak memenuhi unsur pemidanaan.
“Menjadikan Pasal 402 sebagai dasar memidanakan nikah siri adalah tafsir yang sembrono dan tidak sejalan dengan hukum. Bahkan bisa bertentangan dengan hukum Islam,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Prof Ni’am menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi KUHP baru agar benar-benar menghadirkan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan, bukan sekadar menambah daftar pasal pidana.
“Hukum harus memberi perlindungan kepada masyarakat dalam beraktivitas dan menjamin kebebasan umat beragama menjalankan keyakinannya, sesuai ajaran masing-masing,” pungkasnya.***